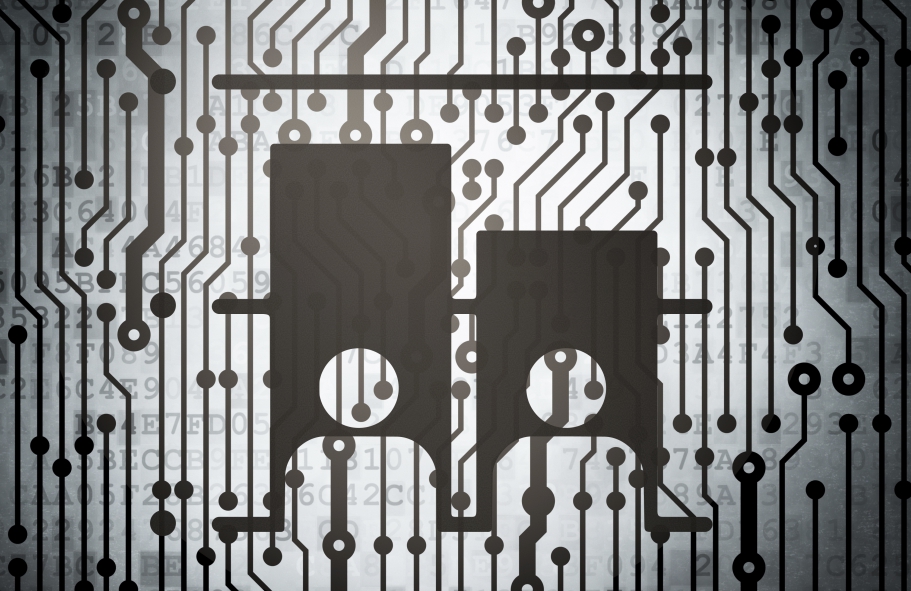Opini Koran Solidaritas, Edisi IX – April 2016
Oleh: Anom Astika*
Di tengah golak-golak macam ragam isu politik yang marak di dalam beberapa bulan terakhir ada dua fenomena penting yang menarik untuk diperhatikan. Pertama, keberanian Ahok untuk maju sebagai calon gubernur DKI lewat jalur independen. Ini sebuah terobosan politik yang baru dan unik. Sebelumnya, sepanjang sejarah pemilihan Gubernur DKI semua calon selalu diusung oleh partai politik. Pun Ahok ketika maju menjadi calon wakil gubernur mendampingi Jokowi di tahun 2012, diusung oleh Partai Gerindra. Namun untuk Pilgub DKI Jakarta mendatang, Ahok sebagai calon petahana seperti tidak menganggap penting dukungan partai politik, dan memilih untuk mengandalkan relawan non partai pendukungnya. Bahkan untuk calon wakil gubernurnya pun Ahok tidak mengambil dari tokoh partai politik, tetapi dari jajaran birokrasi Pemda DKI Jakarta, Heru Budi Hartono. Ada apa sebenarnya antara Ahok dan partai politik?
Partai politik di masa pemerintahan Jokowi tampaknya tidak mendapat tempat yang baik di hati publik. Bukan karena partai-partai politik menghadapi represi dari pemerintah, tetapi justru karena partai politik tidak berperan sebagaimana mestinya, sebagai institusi penganjur etika politik di tingkat praktis. Kasus ‘pencatutan’ nama Jokowi oleh ketua DPR Setya Novanto, dan keputusan Mahkamah Kehormatan DPR di dalam merespon kasus tersebut sedikit banyak melukai hati publik. Kisruh internal yang berlangsung di Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan menunjukkan kepada publik perihal ketidakmampuan partai-partai tersebut di dalam mengorganisasikan dirinya. Bahkan di masa pemerintahan SBY dengan munculnya sejumlah kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik dan pejabat negara, sudah cukup menjadi bagian dari akumulasi sakit hati rakyat saat ini terhadap partai politik.
Dalam konteks DKI, ketika Ahok mulai menjabat sebagai Gubernur DKI menggantikan Jokowi yang terpilih sebagai Presiden RI, muncul kasus korupsi UPS yang diduga melibatkan beberapa oknum dari anggota DPRD DKI Jakarta. Perseteruan antara Ahok dan DPRD pun mencuat dan melahirkan pro kontra di media massa. Bahkan isu UPS diangkat lagi oleh Ahok dalam konteks sekolah rusak di lingkup DKI Jakarta terkait kecilnya anggaran rehabilitasi sekolah di Jakarta dibandingkan dengan anggaran pengadaan pembelian Uninterubtable Power Supplies (UPS), scanner, dan lain-lain. Terakhir, ricuh seputar Reklamasi Teluk Jakarta, yang didahului dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terhadap anggota DPRD DKI, Sanusi dari Partai Gerindra, semakin membuat Ahok maupun publik menjadi tidak bersimpati terhadap keberadaan partai politik.
Fenomena kedua, sebenarnya lebih terkait dengan dunia bisnis dan teknologi komunikasi, tetapi memiliki dampak sosial-politik. Kemunculan generasi baru yang percaya dengan kemampuan teknologi di dalam menyelesaikan problem-problem sosial, ekonomi, dan politik mewujud semenjak berkembangnya pemanfaatan media sosial sebagai media politik publik. Mulai dari urusan promosi produk rumahan sampai dengan gosip intrik politik seputar istana semuanya berkembang di media sosial facebook dan twitter. Bahkan sampai pilpres 2014 kedua jenis media sosial tersebut ramai dengan ‘perang suara’ antara masing-masing pendukung calon presiden.
Tetapi pada periode 2016, semua yang ramai ‘berperang’ di dua jenis media sosial di muka seperti ‘terendam masuk’ ke dalam ruang-ruang publik digital yang lebih privat, yaitu ke dalam grup-grup whatsapp. Kritik dan debat tentang sebuah isu kini lebih marak di dalam berbagai macam grup grup tersebut. Sementara untuk kepentingan ekonomi, promosi produk dan jasa layanan semuanya kini diikat dalam moda-moda aplikasi yang bisa diunduh melalui media komunikasi seluler. Bahkan dalam mekanisme layanan birokrasi masyarakat di DKI Jakarta, gubernur Ahok juga menerapkan sistem aplikasi yang berjaring sampai tingkat kecamatan dan kelurahan.
Efeknya kemudian, di satu sisi layanan birokrasi Pemda DKI Jakarta terhadap persoalan-persoalan riil masyarakat menjadi cepat tertangani, sebagaimana layanan bisnis online pada umumnya terhadap para konsumen. Negatifnya kemudian, dalam konteks layanan jasa transportasi online sebagaimana yang tampil dalam bentuk aplikasi ponsel pintar, GO-JEK, Grab Bike/Car, Uber Taxi telah memunculkan polemik dan aksi massa. Perbedaan pendapat apakah bisnis transportasi online tersebut melanggar UU Perhubungan Darat atau tidak; apakah bisnis transportasi online itu bisnis aplikasi ataukah jasa rental; berikut persaingan antara bisnis jasa transportasi konvensional versus jasa transportasi online, semuanya mengharubiru dalam aksi massa di bulan November 2015 dan Februari 2016. Tetapi segala macam protes dan polemik yang muncul terkait penyelenggaraan bisnis jasa transportasi online tersebut pada akhirnya juga tidak mampu menahan tekanan publik, yang makin lama makin terbiasa dengan teknologi aplikasi.
Problematiknya sekarang dengan segala perkembangan teknologi yang tersedia, apakah partai politik bisa beradaptasi? Jika dunia ekonomi dan birokrasi sudah mampu menyerap teknologi sebagai bagian dari kinerjanya, bagaimana dengan dunia politik dalam hal ini partai politik?
Tugas partai politik bagaimana pun bukan sekedar sebagai sarana penyambung lidah rakyat, dan atau sebagai mediator (wakil rakyat) dari setiap penyusunan kebijakan-kebijakan untuk kepentingan rakyat. Partai politik juga memiliki kewajiban untuk mengajarkan etik dari pencarian/pengupayaan kebenaran yang berpihak kepada rakyat. Partai politik dan atau wakil rakyat tidak mungkin mengupayakan kebenaran jika dirinya tidak memiliki etik untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Pun etik juga tidak berarti sesuatu yang abstrak, karena aturan-aturan maupun norma-norma hukum sebagai turunannya, sudah bisa membimbing partai politik dan atau wakil rakyat untuk memperjuangkan kebenaran. Persoalannya hal etik berpolitik tersebut selalu dilanggar, dan dilanggar sebagaimana kasus-kasus di awal tulisan ini.
Sudah waktunya partai politik memikirkan lebih jauh bagaimana membuat sebuah sistem dan teknologi yang akan membantu kerja kerja mereka di lapangan. Mulai dari teknologi pengambilan data sampai dengan teknologi yang dapat membantu pengambilan keputusan yang berpihak kepada rakyat. Jikalau ini diabaikan, maka fungsi partai politik secara umum tidak akan berbeda jauh dengan grup-grup whatsapp, dan fungsi kerja lapangannya akan bisa dengan cepat digantikan oleh aplikasi-aplikasi android. Ketika itu terjadi, maka de-parpolisasi adalah sesuatu yang tak terhindarkan, dan demokrasi pun pada akhirnya cukup dengan menekan satu tombol di ponsel pintar.
*. Penulis adalah Redaktur Portal Prisma