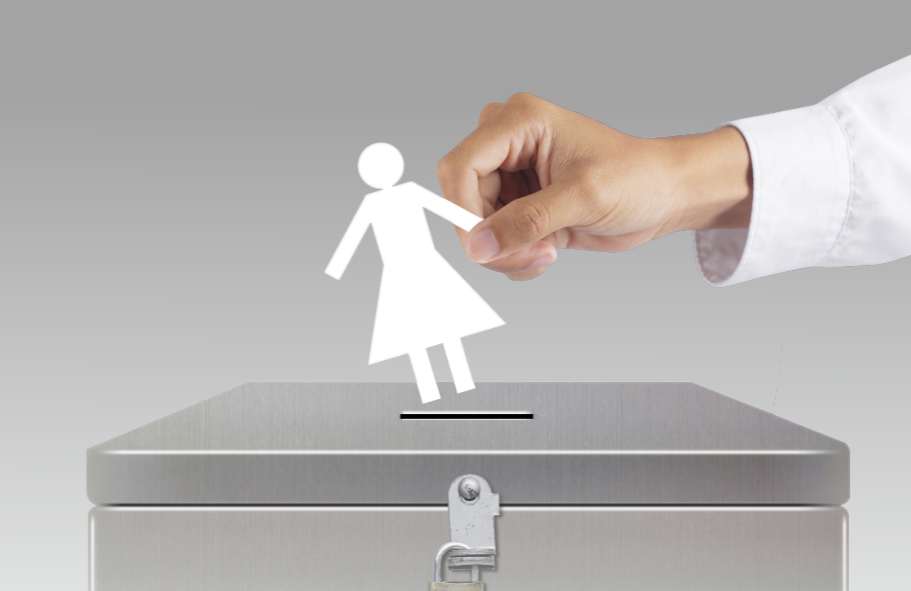Opini Koran Solidaritas, Edisi VIII Februari 2016
Oleh: Titi Anggraini*
Penerapan kebijakan afirmasi (affirmative action) bidang politik, khususnya untuk mendorong lebih banyak perempuan memasuki parlemen, baru mencapai bentuk utuhnya pada Pemilu 2014.
Dalam mengatur kebijakan afirmasi keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% dalam daftar calon, UU No. 8 Tahun 2012 sebetulnya tidak beda dengan UU No. 10 Tahun 2008 yang menjadi dasar penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2009. Namun KPU pada Pemilu 2014 berani memberi makna baru terhadap ketentuan UU No. 8 Tahun 2012, dengan memberikan sanksi tidak boleh ikut pemilu di daerah pemilihan tertentu jika daftar calon di daerah pemilihan itu tidak memenuhi sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan.
Beberapa elite partai politik memprotes adanya ketentuan sanksi administrasi tersebut. Mereka menilai KPU telah melampaui kewenangannya dalam menafsirkan undang-undang. Sebagian lain bahkan mengancam akan mengajukan gugatan peninjauan kembali (judicial review) Peraturan KPU No. 7 Tahun 2013 ke Mahkamah Agung (MA) karena dianggap bertentangan dengan UU No. 8 Tahun 2012. Namun dukungan kuat masyarakat atas peraturan KPU tersebut, meredakan protes dan menyurutkan niat judicial review.
Bagi partai politik jelas lebih realisitis, segera merekrut bakal calon perempuan sebanyak-banyaknya guna memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan dalam daftar calon di setiap daerah pemilihan daripada harus menghadapi opini publik, menunggu dengan cemas putusan MA dan menerima kemungkinan jatuhnya sanksi.
Memang, Bawaslu sempat merevisi keputusan KPU yang memberikan sanksi kepada partai politik untuk tidak ikut pemilu di sautu daerah pemilihan karena dinilai gagal memenuhi kuota 30% keterwakilan. Namun putusan itu tidak bisa menghentikan kesungguhan partai dalam memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan di setiap daerah pemilihan, sehingga akhirnya semua partai di semua daerah pemilihan dinyatakan memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan dalam daftar calon. Sesuatu yang dulu sangat dikhawatirkan oleh partai, tetapi dengan kesungguhan mereka mampu mencapainya.
Kemudian yang jadi kritik adalah partai mencomot begitu saja perempuan yang mau dimasukkan ke daftar calon, lebih-lebih di tingkat kabupaten/kota di mana partai memang tidak pernah berusaha keras menyiapkan kader perempuan. Namun sebagai tahap awal implementasi kebijakan afirmasi, hal itu bisa dimaklumi. Partai memang butuh waktu untuk menyiapkan kader-kader perempuan secara serius setelah peraturan mengharuskannya. Sebab mereka menyadari untuk memenangkan pemilu, mereka tidak bisa sembarangan menampilkan calon anggota legislatif. Apalagi masyarakat semakin mudah mengakses informasi untuk menilai kualitas para calon.
Dalam rangka mengetahui bagaimana partai politik merekrut calon-calon perempuan dalam Pemilu 2014, Perludem pernah melakukan observasi singkat pencalonan perempuan dalam pemilu DPRD kabupaten/kota (Lia Wulandari, dkk: Pencomotan Perempuan Untuk Daftar Calon: Rekrutmen Calon Anggota DPRD Kabupatan/Kota untuk Memenuhi Kuota 30% Perempuan Dalam Pemilu 2014, Perludem, 2014). Lokus observasi sengaja diletakkan di kabupaten/kota, karena partai selalu mengeluhkan sulitnya merekrut kader perempuan di tingkat daerah. Angka keterpilihan perempuan dalam lembaga legislatif daerah yang lebih kecil daripada lembaga legislatif nasional, juga menunjukkan adanya masalah tersebut.
Hasil observasi Perludem menemukan, di tingkat kabupaten/kota, partai politik sesungguhnya kesulitan memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan. Karena mereka tidak memiliki kader perempuan yang mencukupi. Untuk memenuhi kekurangan kader perempuan tersebut, partai mencomot perempuan dari mana saja untuk dijadikan calon demi tercapainya ketentuan kuota 30% keterwakilan perempuan.
Langkah asal comot itu merupakan dampak pertama dari ancaman sanksi yang tegas. Dampak lanjutannya, partai politik di tingkat kabupaten/kota mau tidak harus mempersiapkan kader-kader perempuan dengan baik, agar mereka bisa berkompetisi dalam pemilu mendatang.
Lebih dari separuh perempuan yang masuk dalam daftar calon anggota DPRD kabupaten/kota sesungguhnya menyadari bahwa dirinya hanya sebagai pelengkap daftar calon. Kekurangan pengalaman dan modal menyebabkan mereka tidak melakukan kampanye mencari dukungan pemilih; mereka tidak terobsesi menjadi calon terpilih.
Sementara separuh perempuan yang lain, baik perempuan kader maupun nonkader, bertekad meraih suara sebanyak-banyak agar bisa menjadi calon terpilih. Namun kesungguhan para calon perempuan ini tidak mendapat dukungan sepadan dari partai politik yang mencalonkannya, sehingga mereka cenderung membabi buta dalam mencari suara, termasuk bersiap melakukan jual beli suara.
Dukungan partai politik kepada calon perempuan bukannya tidak ada, tetapi dukungan itu sebatas membantu bakal calon perempuan melengkapai semua persyaratan administrasi pencalonan. Setelah nama-nama perempuan masuk dalam DCT, partai membiarkan mereka bergerak sendiri. Jangankan memberikan dukungan modal dan logistik kampanye, membekali pengetahuan dan ketrampilan berkampanye saja tidak dilakukan partai. Akibatnya banyak calon perempuan berkampanye sekadar meniru calon lain yang belum tentu efektif. Kampanye tanpa strategi ini tentu saja sulit mendulang suara meskipun didukung oleh dana tidak cukup.
Selanjutnya para calon perempuan juga tidak menyiapkan strategi mengamankan perolehan suara, sehingga sangat mungkin perolehan suara mereka akan dicuri oleh calon lain dalam proses penghitungan suara di TPS, PPS, PPK dan KPU kabupaten/kota, sebagaimana terjadi pada pemilu-pemilu sebelumnya. Pembiaran kemungkinan pencurian suara calon perempuan ini, tidak sejak menegaskan bahwa partai politik tidak punya komitmen untuk mendorong perempuan masuk parlemen, tetapi justru kehadirannya hanya digunakan untuk menambah perolehan suara (vote getter).
Rekomendasi
Ada dua rekomendasi yang bisa diberikan atas observasi tersebut. Pertama, rekomendasi untuk pengkajian lebih jauh atas proses dan hasil pencalonan perempuan dalam pemilu DPRD kabupaten/kota, karena temuan observasi yang Perludem lakukan belum memberi gambaran untuh di balik tindakan keterpaksaan partai politik tingkat kabupaten/kota dalam memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan. Beberapa isu yang perlu diteliti lebih jauh adalah hubungan kekeluargaan calon perempuan dengan elit partai politik, kriteria permodalan dalam pemilihan calon, kerjasama dan kompetisi antarcalon perempuan, dan strategis kampanye yang pas buat pemenangan.
Kedua adalah rekomendasi untuk pembuatan kebijakan untuk mendorong pemenuhan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan dalam daftar calon dengan kader-kader berkualitas. Tujuannya agar partai tidak lagi mencomot begitu saja perempuan dicalonkan, tetapi punya keleluasaan untuk memilih kader-kader perempuan berkualitas sehingga kehadirannya dalam daftar calon tidak sekadar memenuhi kuota secara kuantitas tetapi juga kualitas.
Untuk itu beberapa rekomendasi penguatan disampaikan untuk mengokohkan keterwakilan perempuan dalam pemilu kita. Pertama, sanksi administrasi berupa pencoretan status peserta pemilu di daerah pemilihan tertentu jika partai politik gagal memenuhi sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan dalam daftar calon di daerah pemilihan tersebut, perlu dimasukkan ke dalam Undang-Undang Pemilu agar memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat. Pencantuman sanksi tersebut dalam undang-undang tidak perlu dikhawatirkan lagi karena kenyataannya semua partai politik mampu memenuhi ketentuan kuota 30% perempuan di setiap daerah pemilihan, termasuk daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota.
Kedua, sanksi administrasi tidak bisa mengikuti pemilu juga perlu diterapkan kepada partai politik yang gagal memenuhi kuota sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik. Artinya, jika kepengurusan partai nasional gagal memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan, maka partai itu tidak bisa mengikuti pemilu secara nasional; jika kepengurusan partai provinsi gagal memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan, maka partai itu tidak bisa mengikuti pemilu di provinsi, dan; jika kepengurusan partai politik kabupaten/kota gagal memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan, maka partai itu tidak bisa mengiktui pemilu di kabupaten/kota tersebut. Pengaturan sanksi ini bisa dicantumkan dalam undang-undang partai politik maupun undang-undang pemilu. Dengan cara ini maka partai politik di semua tingkatan dipaksa untuk merekrut kader-kader perempuan secara bersungguh-sungguh.
Ketiga, penerapan sanksi tidak bisa mengikuti pemilu, baik pada tingkat wilayah pemilu maupun daerah pemilihan, bagi partai yang gagal memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan, perlu juga diimbangi oleh kompensasi atau reward kepada partai politik yang mampu melampaui kuota 30% keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik maupun dalam daftar calon. Misalnya, partai politik yang menyertakan 40% pengurus perempuan, maka surplus 10% tersebut bisa dikompensasi dengan bantuan keuangan partai politik lebih banyak daripada partai yang hanya pas memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan dalam kepengurusan.
Demikian juga partai politik yang menyertakan 50% calon perempuan dalam daftar calon, maka surpulus 20% tersebut bisa dikompensasi dengan bantuan dana kampanye, yang bisa diwujudkan dalam bentuk fasilitas kampanye gratis di media penyiaran publik. Kompensasi ini akan mendorong partai politik berlomba-lomba merekrut kader-kader perempuan. Demikian.
*) Penulis adalah Direktur Eksekutif Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)