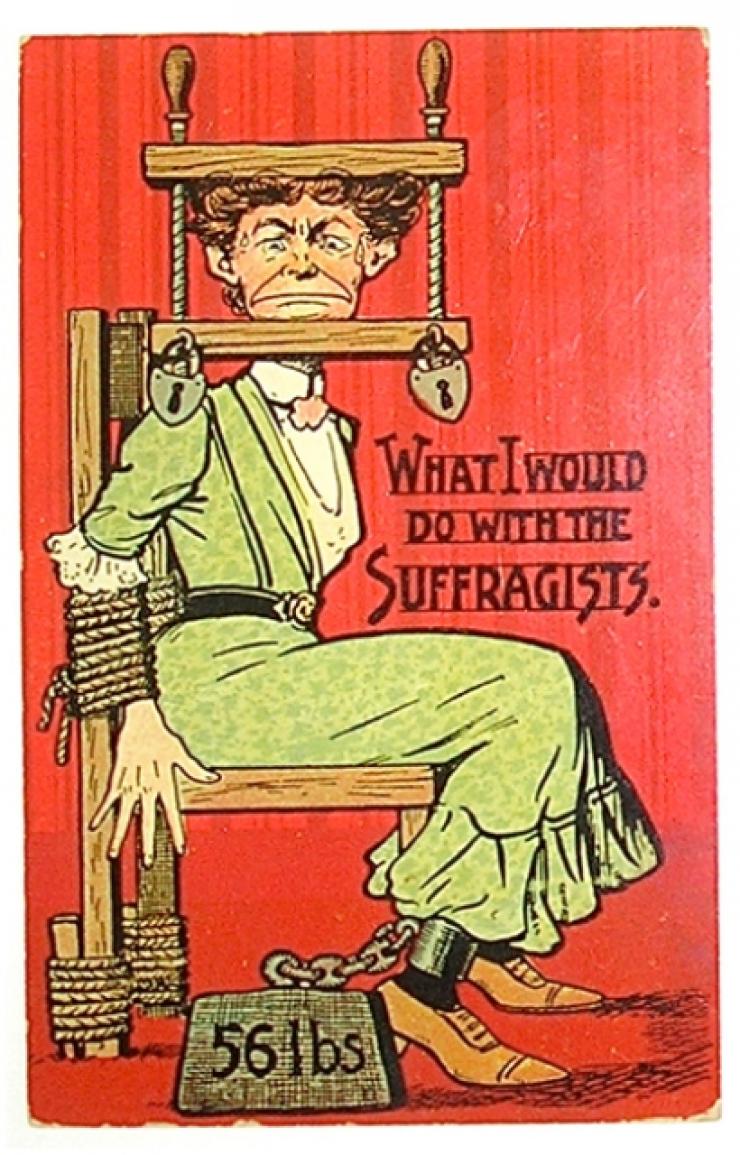Reformasi Partai dan Politik Perempuan
Pengantar:
Esai ini merupakan salah satu karya peserta Lomba Esai “Anak Muda dan Politik” yang diselenggarakan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) bekerja sama dengan Qureta pada 2016.
Oleh: Arjuna Putra Aldino
Mungkin bukan sesuatu yang baru soal keterwakilan politik perempuan dalam panggung politik elektoral Indonesia. Berbarengan dengan hiruk pikuk pesta demokrasi lima tahunan, kalangan aktivis perempuan tampaknya lebih fokus dan konsisten untuk memperjuangkan kuota 30 persen representasi politik perempuan sebagai agenda perjuangan bersama.
Perjuangan politik perempuan dimaknai dengan perjuangan meraih kursi di parlemen. Dengan asumsi, apabila perempuan berhasil meraih kursi sebesar 30 persen maka perempuan mampu mempengaruhi kebijakan-kebijakan negara. Atau kebijakan negara yang dulu kental diwarnai narasi-narasi politik laki-laki dapat diisi dengan pikiran-pikiran politik berbasis gender.
Geliatnya pun mengemuka, nyaris semua elemen perempuan dari aktivis hingga selebriti mengarahkan hampir seluruh energi politiknya ke satu titik yakni mengupayakan representasi politik perempuan yang lebih proporsional, adil, dan setara. Dan bukan hal yang aneh pula, wacana representasi politik perempuan kian nyaring dan menggema bukan tanpa sebab, melainkan sejalan dengan bergulirnya “liberalisasi politik” pasca reformasi 1998.
Tak salah memang, hal ini merupakan respon dari politik rezim orde baru yang otoritarian dan hegemonik dimana kultur “politik lelaki” menjadi struktur atas dari bangunan budaya politik rezim ini. Perempuan diperbolehkan melakukan peran sosial-politiknya,akan tetapi di bawah kendali ketat negara korporatis.
Budaya politik Orde Baru yang kental dengan corak “bapakisme” membuat gerakan perempuan menjadi ewuh pekewuh untuk lebih tampil dan berperan dalam kehidupan bernegara. Bahkan gerakan perempuan nyaris tenggelam di arus kekuasaan yang berwatak patrimonial. Isu-isu keadilan gender tertelan oleh wacana stabilitas politik dan pembangunan. Tak hanya itu, gerakan perempuan di era ini, justru menjadi bagian yang integral dari kekuasaan rezim.
Organisasi perempuan seperti Kowani, Dharma Wanita, Dharma Pertiwi dan PKK hanya menjadi corong Orde Baru, seperti mendukung program keluarga berencana dan mendukung Golkar untuk memenangkan pemilihan umum selama Orde Baru berkuasa 36 tahun. Gerakan perempuan tak lekang dari upaya kontrol dan memperkokoh kekuasaan rezim.
Bahkan di era ini, ada tiga konsep yang digalang oleh Kowani yaitu Istri, Ibu dan Pelayan Negara, dimana Kowani sebagai mitra orde baru bersama organisasi istri pegawai negeri dan istri korp militer bergabung memperkuat rezim Orde Baru dibawah naungan Golkar. Wajar jika pasca rezim otoritarian tumbang gerakan wanita yang menyuarakan keterwakilan politik perempuan dalam panggung politik mulai bersemai dan bergema keras. Namun hal ini tak juga luput dari masalah.
Ketika kuota 30 persen representasi politik perempuan sudah berhasil di raih, ia terbentur oleh permasalahan yang juga menghinggap demokrasi elektoral kita. Data Puskapol UI menunjukan bahwa 36% anggota legislatif perempuan terpilih karena politik kekerabatan dengan elit yang berkuasa.
Caleg perempuan yang menang umumnya adalah figur yang memiliki jaringan kekerabatan dengan elit politik dan elite ekonomi. Sebagian besar dari mereka adalah adik, kakak, ataupun istri dari penguasa/pejabat politik, elite ekonomi serta petinggi partai politik yang mencalonkan mereka.
Fenomena ini juga menandakan sempitnya landasan rekruitmen caleg perempuan oleh partai. Rekruitmen caleg perempuan tak di ukur melalui intensitas keterlibatan caleg secara aktif dalam partai termasuk juga rekam jejak selama menjadi anggota partai serta kompetensi mereka dalam memperjuangkan aspirasi politik masyarakat. Namun semata-mata hanya mencakup hubungan kekeluargaan melalui pernikahan (isteri pejabat politik ataupun petinggi partai politik) serta anak-anak dan saudara mereka.
Akibatnya perjuangan kesetaraan gender melalui keterwakilan politik perempuan dalam panggung politik justru terperosok dalam perangkap politik dinasti. Didominasinya basis keterpilihan caleg perempuan berlandaskan kekerabatan justru menegaskan ketergantungan perempuan pada basis kekuasaan laki-laki. Sehingga yang ada justru pelestarian relasi kuasa yang senjang secara politik maupun sosial antara perempuan dan laki-laki.
Akhirnya kehadiran perempuan dalam politik sebatas menjadi fungsi penggalang suara dalam upaya merebut kekuasaan dan memenangkan kontes pemilihan umum. Perjuangan politik perempuan hanya diperalat oleh drama para elite politik. Sehingga keterwakilan perempuan dalam politik hanya sekedar ada, semata-mata hanya sekedar memenuhi kuota.
.Di tengah kondisi semacam ini, sulit kita berharap perempuan untuk bersuara kritis dan menghasilkan kebijakan-kebijakan politik yang mengarah pada emansipasi perempuan. Kenyataannya, implementasi politik perempuan masih hanya sebatas pemenuhan syarat administratif agar partai dapat meloloskan diri untuk ikut dalam pemilu.
Membidik Persoalan dan Mencari Penyelesaian
Tingginya ketergantungan politik perempuan pada basis kekuasaan laki-laki merupakan akibat logis dari adanya “politik kekerabatan” dalam basis rekruitmen calon legislatif. Namun adanya politik kekerabatan dalam basis rekruitmen calon legislatif, juga bagian dari akibat sempitnya landasan rekruitmen calon legislatif yang dilakukan oleh partai. Bahkan hal ini bisa dikatakan sebagai sebuah pertanda adanya “stagnasi” proses kaderisasi di dalam partai politik. Dengan kata lain, mesin kaderisasi didalam partai politik mengalami kemandekan. Sehingga landasan rekruitmen pun mengalami penyempitan, hanya sebatas kekerabatan.
Namun hal ini tak bisa dilepaskan dari persoalan adanya konsentrasi kekuasaan di tangan segelintir elite di dalam partai. Dengan adanya konsentrasi kekuasaan di tangan segelintir orang di dalam partai membuat pencalonan pejabat publik yang diusung oleh partai politik mengabaikan kriteria pemimpin ideal yang dibutuhkan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan publik.
Atau bisa dikatakan rekruitmen wakil rakyat tidak berlandaskan pada kapabilitas dan integritas seseorang namun kaderisasi dan rekruitmen didalam partai hanya sebuah wujud dari “patronase politik” dimana rekruitmen politik pada kenyataannya lebih merupakan praktek kompetisi di antara berbagai jaringan patron-klien.
Sehingga mereka yang tidak memiliki koneksi dengan orang dalam seperti kelompok-kelompok minoritas, ataupun mereka yang tidak memiliki apa pun untuk ditawarkan kepada sang patron, tak mampu bersaing di arena politik. Maka hal ini mengakibatkan rekruitmen yang dilakukan oleh partai rawan dengan politik transaksional yang hanya melibatkan segelintir orang di dalam partai.
Bahkan yang paling berbahaya, mereka yang berkuasa cenderung akan menyingkirkan setiap kemungkinan munculnya kontestasi, terutama dari elite alternatif yang ingin melakukan manuver perubahan. Para penguasa dengan sekuat tenaga akan menghambat munculnya jenis aktor baru yang berpotensi menandingi kekuasaannya. Sehingga partai politik mengalami atrophia (kemandekan) bahkan “patologi struktural” yang mengarah pada kecacatan di dalam tubuhnya sendiri.
Untuk itu, jalan satu-satunya untuk mengubah hal ini yakni adanya perubahan didalam tubuh partai politik itu sendiri. Terutama diselenggarakannya demokrasi didalam internal partai untuk memecah terkonstrasinya kekuasaan ditangan segelintir orang yang berkuasa didalam partai. Dengan kata lain, partai politik sebagai pilar demokrasi, juga harus melakukan upaya demokratisasi didalam internal dirinya sendiri.
Begitu pula mendesak untuk dilakukannya reformasi internal partai politik yang mengarah pada perluasan basis rekruitmen perempuan yang berlandaskan pada representasi politik. Sehingga partai politik benar-benar dapat menghadirkan kepentingan perempuan.
Hal ini juga penting mengingat politik saat ini mengandung bahaya adanya “privatisasi politik” dimana kebijakan publik yang diambil oleh para pemegang kekuasaan seringkali hanya diperuntutkan untuk kepentingan dirinya. Bukan untuk kebaikan orang banyak (common good). Artinya, upaya ini penting untuk mengembalikan politik kepada makna harafiahnya sebagai upaya bersama mengatur kehidupan publik.
Arjuna Putra Aldino
Peneliti
Lomba Esai Politik PSI-Qureta Juara Kedua
Lomba Esai Politik PSI ini bekerja sama dengan Qureta, diselenggarakan 20 Agustus-05 Oktober 2016. Dewan juri memutuskan tiga orang juara, yakni juara 1, 2, dan 3, serta tujuh juara harapan